Memahami
fenomena sosial-budaya Madura tidak bisa hanya dari yang tampak di permukaannya
saja, karena hal itu bukan bukan hanya tidak memadai, melainkan bisa
menyesatkan. Begitulah Jamal D. Rahman menulis di pengantar buku ini. Menurut
saya, ini penting untuk dijadikan pegangan oleh siapa saja yang memiliki
keinginan mengaji/mengkaji tentang Madura. Karena sejatinya, Madura dengan
aneka warna yang ditampakkannya tidak sedangkal yang terlihat secara kasat
mata, tetapi mengandung sisi lain yang subtil, dan itu hanya bisa dijangkau
dengan menyelam ke dalamnya.
Buku ini adalah pintu untuk mengenal
Madura dengan kacamata keadilan. Esai-esai Kiai A. Dardiri Zubairi selain
mengungkap tentang makna dari beberapa budaya dan kearifan lokal Madura, juga
sebagai respon atas stereotip “keras” yang sampai saat ini masih melekat kuat
bagi orang Madura. Bahkan ada beberapa kejadian, orang luar mencari
perlindungan di balik nama Madura agar bisa selamat dari gangguan yang
menyerangnya. Bagi masyarakat luar, suku Madura dengan lambang celuritnya
identik dengan carok yang semakin menguatkan stereotip itu sehingga terus
beranak-pinak dari generasi ke generasi.
Pada dasarnya, lembaga pendidikan
juga memiliki tanggung jawab untuk mewarisi kearifan lokal masyarakat setempat
agar tetap lestari. Kiai A. Dardiri dalam buku ini menyebutkan pesantren
sebagai penenun keislaman yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan
masyarakat Madura. Maka sangat disayangkan jika peneliti asing, salah satunya
Huub de Jonge tidak melibatkan pesantren dalam memahami Madura dengan sekelumit
persoalannya. Karena kata penulis, memisahkan pesantren dengan Madura ibarat
memisahkan ikan dan air. Madura akan pucat, dan pelan-pelan kehilangan nyawa.
Agama dan kebudayaan adalah dua hal
yang saling melengkapi. Hal itu dapat dipahami dari pakaian lokal masyarakat
Madura, yaitu sarung dan songkok. Dua pakaian ini memiliki nilai kearifan yang tidak
bisa dilihat secara literal, tetapi perlu ada upaya menyelam secara mendalam
agar dapat memahami nilai-nilai yang dikandungnya. Bagi orang Madura, songkok
bukan sekadar penutup kepala, lebih dari itu songkok dianggap sebagai simbol
tatakrama. Ketika menyambut tamu, yang diambil pertama kali adalah songkok.
Bahkan kakek saya sendiri, saat mau makan pasti memakai songkok meski tidak
sedang mengenakan baju, hanya celana pendek/sarung.
Awalnya, songkok putih hanya
dikenakan oleh orang yang datang haji. Itu merupakan lambang kesucian karena
baru saja menyempurnakan rukun Islam yang terakhir. Status haji adalah tangga
spiritual yang seharusnya ditempuh dengan sepenuh hati. Maka, masyarakat Madura
mempunyai plesetan unik terhadap orang yang sudah naik haji tetapi tetap
berkutat dengan perilaku-perilaku yang kurang baik. Orang Madura menyebutnya “Ji
tasbani”, itu merupakan singkatan dari “attassa ajji, baba banne”
(atasnya haji, bawahnya bukan). Jadi, naik haji adalah proses penyucian diri
agar semakin dekat dengan Sang Ilahi.
Begitu pula sarung. Kiai A. Dardiri
mengungkapkan, songkok sebagai sahabat karib sarung. Sejak anak belajar mengaji
ke surau/langgar, ia sudah dibiasakan mengenakan sarung oleh orang tua mereka
masing-masing. Bahkan sarung yang biasa dikenakan masyarakat Madura, laki-laki
maupun perempuan, bukan sekadar pakaian khas, tetapi juga menjadi ekspesi
keagamaan yang ramah budaya. Sekali lagi, agama dan budaya memang seharusnya
berjalan beriringan, saling mengisi bukan sebaliknya malah diseret pada ruang
kompetisi.
Terlepas dari itu, ada kebiasaan
mulia orang Madura, yaitu ser maleng, sebuah kebiasaan memberi secara
sembunyi, tanpa menampakkan identitas agar tidak diketahui orang, baik yang
menerima pemberian maupun orang lain. Senada dengan ungkapan “lempar batu
sembunyi tangan”. Untuk menjaga keikhlasan, ser maleng menjadi suatu
tradisi masyarakat Madura, yang sepertinya saat ini sudah mulai berkurang, atau
bahkan hilang. Di zaman yang sudah serba pragmatis dengan dunia elektronik yang
tinggi, manusia cenderung ingin diakui dan diketahui, baik dalam dunia nyata
maupun dunia maya. Selain itu, masih banyak tradisi-tradisi di Madura yang
sarat dengan nilai kearifan.
Perempuan Madura sebagaimana perempuan pada umumnya, memiliki karakteristik cantik sesuai selesra kulturalnya. Penulis menegaskan bahwa Madura dengan segenap cita rasa kulturalnya, punya referensi tersendiri tentang perempuan cantik, yaitu: “potre koneng potre Madura, pajalannan neter kolenang, palembayya meltas manjalin, matana morka’, alessa daun membha, bibirra jerruk salone”. Terjemahan bebasnya: potre koneng (nama istri raja) putri Madura, cara berjalan sungguh gemulai, selentur kayu rotan, matanya lentik, alisnya seperti daun mimbha, bibirnya bak seiris jeruk. Ungkapan tersebut tidak sebatas menyinggung perempuan secara fisik, tetapi memiliki makna substantif yang menarik untuk dikaji. Cantik versi orang Madura lebih menekankan pada isi, yang dikenal dengan ungkapannya, “raddin atena, bagus tengka gulina” (cantik hatinya, indah perilakunya).
Kumpulan esai dalam buku ini, ditulis berdasar pada pemahaman dan pengalaman penulis sendiri, sehingga menjadikan tulisan ini kaya dengan informasi kemaduraan yang tidak banyak diketahui masyarakat luar. Atau jangan-jangan, kemajuan zaman telah berhasil mengelabuhi masyarakat Madura dan membuat mereka justru merasa asing dengan nilai-nilai kearifan yang semula dijaga dan dilestarikan. Jika itu yang terjadi, sungguh naif sekali.











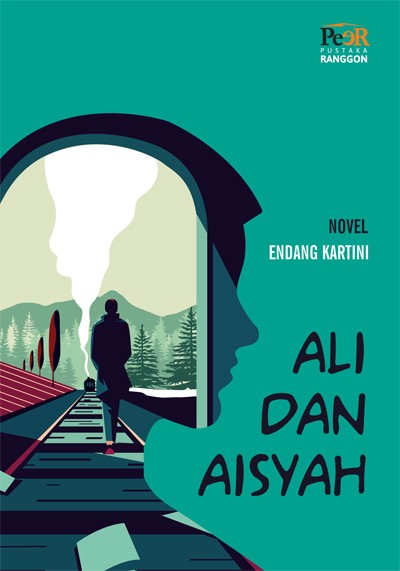

0 Komentar