 |
| sumber: khazanahfikiranku.blogspot.co.id |
Pendahuluan
Masyarakat pra-Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliyah. Dalam
satu sisi masyarakat Jahiliyah dikenal dengan
masyarakat yang tidak tahu baca-tulis (ummy). Sementara pada masa
itu, terdapat dua imperium besar yaitu Persia (terletak di bagian timur) dan
Romawi (terletak di bagian barat). Dua imperium tersebut memiliki kekuatan dan
peradaban besar, yang dalam satu sisi lebih tinggi dari orang-orang Arab,
termasuk dalam tradisi tulis-menulisnya.
Namun pada kenyataannya, sejak dulu bangsa Arab dikenal dengan
bangsa yang suka berdagang (saudagar). Salah satu kafilah yang sering melakukan
perjalanan ke daerah-daerah sekitar, misalnya ke Syam, ke Irak atau ke
daerah-daerah Arab lainnya ialah Abu Sufyan bin Umayyah serta ia tercatat
sebagai tokoh yang pertama belajar baca-tulis di Hirah.[1]
Maka menurut interpretasi sejarah, tidak heran jika di samping ia berdagang, ia
juga belajar kepada orang-orang Hirah tentang membaca dan menulis, yang pada
akhirnya diajarkan pada kaumnya di Makkah.
Dari proses belajar membaca dan menulis inilah lahirlah sebuah istilah
maktab dan kuttab sebagai lembaga pendidikan dasar yang
memberikan ruang untuk belajar baca-tulis. Pada awalnya, sebutan kuttab
menunjukkan bahwa ia telah ada pada abad pertama dalam Islam.[2]
Akan tetapi, menurut Asma Hasan Fahmi yang dikutip oleh Mira Astuti dalam Nizar
mengatakan bahwa keberadaan maktab dan kuttab memiliki arti yang
sesungguhnya sejak ada Islam, karena keberadaannya sebelum Islam masih kurang
popular. [3]
Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa maktab dan kuttab
memiliki peran penting mulai pra-Islam sampai Islam datang dan berkembang
dengan pencapaian ilmu pengetahuan yang gemilang.
Lembaga pendidikan maktab dan kuttab ini, senantiasa
mengalami perkembangan mulai dari masa awal Islam sampai pada masa dinasti
Umayyah, setidaknya sejak masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya
al-Walid bin Abdul Malik, dan mencapai puncaknya pada masa bani Abbasiyah. Di
sinilah madrasah-madrasah sudah didirikan sebagai lembaga pendidikan menengah
setelah kuttab dengan corak dan model pendidikan yang berbeda dari
sebelumnya.[4]
Maka dari itu, keberadaan lembaga pendidikan maktab dan
kuttab menjadi sangat penting untuk dikaji ulang, mengingat implikasi dari
proses pendidikannya cukup untuk menjadi bekal pada proses pendidikan
setelahnya. Sehingga dalam hal ini,
penulis berupaya mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendidikan dasar di maktab
dan kuttab dalam perspektif historis.
Pengertian Maktab dan Kuttab
Pada dasarnya, maktab dan kuttab merupakan
dua kata yang berbeda dari segi bahasa, tetapi secara istilah keduanya memiliki
arti yang sama. Maka, dalam
pengertian etimologi kata maktab merupakan bentuk isim makān dari
wazan kataba-yaktubu, yang berarti tempat menulis. Sedangkan mengenai
kuttab Ahmad Syalabi memberikan pengertian bahwa asal mula kata kuttab
ialah taktībun yakni al-kuttābu min al-taktībi wa ta’līmi al-kitābati.
Maksudnya kuttab berasal dari kata at-taktīb yang artinya
pengajaran menulis. Dalam lisān al-‘arabiyah yang dikutip oleh Ahmad
Syalabi dikatakan bahwa: al-kuttābu maudhi’u ta’līmi al-kitābi, artinya kuttab
adalah tempat pengajaran menulis.[5]
Akan tetapi, secara istilah maktab dan kuttab
diartikan sama yaitu sebagai tempat pembelajaran menulis.[6]
Dalam aktivitas menulis, sudah tentu dilakukan pula aktivitas membaca. Karena,
membaca dan menulis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dengan
kata lain menulis tidak bisa dilakukan tanpa aktivitas membaca terlebih dahulu.
Sehingga pada proses selanjutnya maktab dan kuttab lebih dikenal
sebagai tempat pembelajaran baca-tulis. Maktab atau kuttab
biasanya hanya digambarkan sebagai sekolah pada pendidikan dasar. Itu merupakan
kebenaran bahwa pendidikan sekolah dimulai di maktab, yang mana di dalamnya di ajari seni sastra seperti proaedeutic untuk dua bagian
pengetahuan: ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan asing.[7]
Maktab atau kuttab
(tulis sekolah. Maktab, sebagai
tempat pengajaran menulis, telah ada dalam dunia Arab sebelum Islam. Itu
sebenarnya sebuah tempat untuk belajar membaca maupun menulis, lokasinya di
rumah guru yang mana murid dikumpulkan
untuk kegiatan pembelajaran. Ada juga jenis-jenis lain dari maktab,
setelah kedatangan Islam,
pembelajarannya tidak hanya al-Qur’an dan agama. Seperti kuttab dari Abu al-Qasimal-Balkhi
(w. 723; 105 A.H.) terdapat sekita 3000 murid. Pengajar pada maktab tersebut di sebut mu’allim
atau guru.[8]
Pada awalnya, pembelajaran di maktab dan
kuttab hanya berkisar tentang bahasa-bahasa yang digunakan berupa syair-syair
atau pepatah-pepatah khususnya bagi yang pengajarnya nonmuslim.[9] Sehingga Menurut al-Baladziri dalam Syalabi
mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Islam datang, hanya ada 17 orang Quraisy
di Makkah yang tahu baca-tulis. [10] Hasan
Asari dalam Baharuddin, et.al. menambahkan bahwa di Madinah orang yang tahu
baca-tulis hanya berjumlah 11 orang. [11]
Padahal pada saat itu, Islam sangat membutuhkan orang-orang yang pandai membaca
dan menulis sebagai tuntutan situasi yaitu untuk menulis wahyu.
Secara substantif, istilah maktab dan kuttab sesuai
dengan pengertiannya yaitu sama-sama merujuk pada lembaga pendidikan dasar
sebagai aktivitas belajar membaca dan menulis. Berkenaan dengan itu, ada tokoh yang
membedakan dua istilah tersebut yaitu adalah Abdullah Fajar dalam Engku dan
Zubaidah mengatakan bahwa maktab adalah istilah pada zaman klasik,
sedangkan kuttab adalah istilah untuk zaman modern.[12]
Dalam pandangan penulis, argumentasi Abdullah Fajar mengenai perbedaan
maktab dan kuttab kurang memberikan batasan-batasan yang jelas, sejak
dan sampai kapan dikatakan sebagai periode zaman klasik yang menggunakan
istilah maktab sebagai tempat belajar membaca dan menulis, serta sejak
kapan pula beralih pada istilah kuttab yang dikatakan sebagai istilah
untuk zaman modern. Seperti halnya saat ini, yang dikenal sebagai zaman modern,
akan tetapi persoalannya tidak ada sebutan kuttab pada lembaga
pendidikan dasar. Maka, penulis lebih cenderung mengatakan sama, yakni maktab
dan kuttab tetap dialamatkan pada tradisi awal tulis menulis yang
terjadi di masa pra-Islam sampai Islam datang dan berkembang. Jadi, pada abad
kedua dan seterusnya maktab dan kuttab sebagai lembaga pendidikan
dasar mengalami banyak perkembangan hingga mencapai puncaknya pada masa bani
Abbasiyah.
Sebenarnya, pada masa bani Umayyah lokasi maktab dan kuttab
tidak hanya di samping-samping masjid, tetapi dilaksanakan di istana-istana
raja, untuk mengajari baca-tulis putra-putri raja. Perkembangan ini terjadi
mulai dari pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya al-Walid bin Abdul
Malik.[13]
Model pembelajaran di maktab dan kuttab sudah lebih kompleks dari
pada sebelumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu.
Sementara pada masa bani Abbasiyah, maktab dan kuttab sudah
tertata dengan baik dalam bentuk madrasah. Maka dalam hal ini dapat dipahami
bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah maktab dan kuttab.
Sehingga, jika maktab dan kuttab menjadi lembaga pendidikan
dasar, madrasah merupakan lembaga pendidikan menengah.[14]
Dengan demikian pada masa ini, sudah didirikan madrasah-madrasah sebagai
lembaga pendidikan menengah atau lanjutan setelah mendapat predikat “lulus”
dari maktab dan kuttab. Karena baca-tulis merupakan dasar untuk
belajar ilmu-ilmu yang lain. Berdirinya madrasah pada masa ini disebabkan oleh
terjadinya persentuhan dengan budaya-budaya Yunani, yang mana di Yunani telah
dikenal istilah-istilah sekolah dengan sebutan “scole” yang berarti
“waktu senggang”.[15]
Sedangkan Menurut Mira Astuti dalam Nizar keberadaan maktab dan
kuttab mengalami perubahan yaitu perubahan bentuk dan fungsi mulai dari
masa awal Islam sampai pada masa al-khulafau ar-rasyidun. Perubahan
tersebut secara umum ialah para guru mengajar tanpa ada bayaran (sukarela),
karena kondisi pada masa itu masih belum stabil. Akan tetapi, pada masa bani
Umayyah ada di antara para penguasa yang sengaja menggaji guru untuk mengajar
putra-putranya dan menyediakan tempat di istananya.[16]
Di samping itu, ada sebagian kecil yang masih mempertahankan bentuk
lama yaitu pelaksanaan pendidikannya berlangsung di sekitar masjid untuk murid
yang kurang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Karena pelaksanaan pendidikan
semacam itu, mengikuti masa awal Islam sampai pada masa al-khulafau ar-rasyidun
yakni guru hanya mendapat penghargaan dari masyarakat tanpa dibayar. Sementara
perubahan dari segi fungsi dapat dilihat dari fokus pendidikannya yang hanya
mengarah pada pembelajaran baca-tulis sampai pada mengajarkan al-Qur’an dan
dasar-daar keagamaan.[17]
Sistem
Pendidikan Dasar di Maktab dan Kuttab
Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia Islam sebelum muncul lembaga
pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, sebenarnya telah berkembang
lembaga pendidikan Islam yang dikategorikan sebagai lembaga pendidikan
nonformal. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa
unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan beberapa unsur tersebut
bersifat inhern demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang dikehendaki.
Menurut Phill K. Hitti yang dikutip oleh Mira Astuti dalam Nizar
mengatakan bahwa kurikulum pendidikan di maktab dan kuttab ini
berorientasi pada al-Qur’an sebagai text book. Hal ini mencakup
pengajaran membaca dan menulis, kaligrafi, gramatikal bahasa Arab, sejarah Nabi
dan hadits Nabi saw.[18]
Jadi, sesuai dengan orientasi kurikulum tersebut tujuan umum yang ingin dicapai
dalam proses pendidikan di maktab dan kuttab ialah murid dapat
membaca dan menulis yang penekanannya pada al-Qur’an, dapat memahami
dasar-dasar ilmu agama serta mampu mengamalkannya.
Aktivitas pembelajaran juga
diselenggarakan di istana raja dan selain
kurikulum pada maktab,
pembelajaran yang telah diberikan ialah ilmu sosial dan budaya kebutuhan
mempersiakan pendidikan tinggi, untuk kalangan yang halus budi pekertinya, dan
seringkali sebagai jasa pada pemerintah dan khalifah. Pada kenyatannya, para guru di sekolah
istana, dipanggil mu’addib dari
kata adab,
atau tatakrama yang baik. Muaddib berarti orang yang memiliki tatakrama
baik. Seni pidato dan
percakapan yang baik, etika formal dan
beberapa sejarah dan tradisi yang
juga termuat dalam kurikulum.[19]
Pada dasarnya, setiap anak
dengan tabiatnya cenderung untuk meniru segala sesuatu (baik dari cara guru
berpikir dan bertindak). Sedang guru adalah orang yang paling dekat dengan
murid sesudah orang tua. Begitupun anak-anak yang menghabiskan waktunya di kuttab
menyerap sebagian besar kebiasaan dari tingkah laku guru-gurunya. Dari
sinilah, para pendidik (guru) harus mulai mengarahkan usahanya untuk membina
hubungan yang harmonis antara guru dan murid serta guru harus menunjukkan
perilaku yang baik kepada mereka. Karena, guru yang membimbing kemampuan akal
dan keagamaannya, sehingga terbentuk perubahan anak berdasarkan
kebiasaan-kebiasaan yang baik dan di dalam jiwanya tertanam tata nilai yang
mendasari perjalanan hidupnya.[20]
Menurut Hasan Abd al-‘Ali dalam Baharuddin
menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan yang dipakai dalam maktab dan kuttab
hingga abad ke-4 H. masih sangat sederhana dan menunjukkan penekanannya pada
pelajaran baca-tulis al-Qur’an bagi anak-anak kaum muslim.[21] Akan
tetapi, sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa dari masa ke masa maktab
dan kuttab sebagai lembaga pendidikan dasar senantiasa mengalami
perkembangan. Hal itu juga berpengaruh pada tujuan yang ingin dicapai.
Perkembangan pembelajaran di maktab dan kuttab diwujudkan dengan
memperluas materi yang diajarkan, seperti halnya pembelajaran memanah,
menunggangi kuda serta berenang. Oleh karenanya, tujuan yang ingin dicapai juga
bertambah luas, yaitu selain pandai baca-tulis al-Qur’an, dasar-dasar
keagamaan, juga memiliki kemampuan dalam bidang psikomotorik.
Pada abad ke 8 M. maktab dan kuttab mulai mengajarkan
pengetahuan umum di samping ilmu agama. Hal ini terjadi akibat adanya
persentuhan antara Islam dengan warisan budaya helenisme sehingga banyak
membawa perubahan dalam bidang pendidikan agama Islam. Bahkan dalam
perkembangan berikutnya, maktab dan kuttab dibedakan menjadi dua:
maktab dan kuttab yang mengajarakan pengetahuan nonagama (secular
learning) dan pengetahuan agama (religious learning). Dengan adanya
perubahan kurikulum tersebut dapat dikatakan bahwa maktab dan kuttab pada
awal perkembangan merupakan lembaga pendidikan yang tertutup dan pasca
terjadinya persentuhan dengan peradaban helenisme menjadi lembaga pendidikan
yang terbuka terhadap berbagai rumpun pengetahuan umum, termasuk filsafat. [22]
Urgensi pendidikan baca-tulis sebagaimana yang dilaksanakan di maktab
dan kuttab memberikan kontribusi tersendiri yang mendasari
perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah Islam mencatat, bahwa di zaman klasik,
pertengahan dan di masa sekarang terdapat sejumlah institusi pendidikan Islam
yang memiliki kekuatan serta telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi
perkembangan intelektual, kebudayaan dan peradaban Islam.[23]
Selain itu, kepandaian membaca dan menulis dalam kehidupan sosial dan politik
umat Islam memiliki peranan penting sebagai media komunikasi dakwah kepada
bangsa-bangsa di luar bangsa Arab dan dalam menuliskan berbagai macam
perjanjian. Sedangkan pada masa al-khulafau ar-rasyidun dan masa-masa
selanjutnya, baca-tulis digunakan dalam komunikasi ilmiah dan berbagai buku
ilmu pengetahuan.[24]
Lembaga ini (maktab dan kuttab) dipandang sebagai
media utama untuk mengajarkan membaca dan menulis al-Qur’an dan dasar-dasar
keagamaan. Sedangkan materi-materi yang diajarkan diserahkan sepenuhnya kepada para
guru. Dalam rangka mencapai suatu tujuan, maka penyajian materi hendaknya
disampaikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan dengan menggunakan teknik
pembelajaran yang sesuai.
Untuk itu, diperlukan metode atau
teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi agar tujuan mudah tercapai. Maka,
menurut Rahmawati Rahim yang dikutip oleh Mira Astuti dalam Samsul Nizar
menyimpulkan bahwa metode atau tehnik pembelajaran yang digunakan pada lembaga
pendidikan maktab dan kuttab ialah sebagai berikut:
1.
Metode lisan. Metode ini berupa dikte (imla’),
ceramah, qira’at dan diskusi.
2.
Metode menghafal. Metode ini merupakan ciri umum pendidikan
masa ini. Murid-murid harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya sampai
melekat pada benak murid-muridnya.
3.
Menulis. Metode ini
dianggap sebagai metode yang paling penting, karena merupakan pengkopian
karya-karya ulam, sehingga terjadi proses intektualisasi hingga tingkat
penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga sebagai alat
penggandaan buku-buku teks, karena masa ini belum ada mesin cetak. Sehingga
dengan pengkopian buku-buku, kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi.[25]
Dalam operasionalnya, pelaksanaan
pembelajaran di maktab dan kuttab dilakukan dengan sistem
halaqah, namun ada juga guru yang menggunakan metode yakni membacakan sebuah
kitab dengan suara keras, kemudian diikuti oleh seluruh muridnya. Proses ini
dilakukan berulang-ulang sampai murid benar-benar menguasai materi yang
diajarkannya. Sedangkan lama belajar di maktab dan kuttab
tersebut tidak dibatasi oleh waktu, akan tetapi ditentukan oleh kemampuan siswa
dalam menyelesaikan pelajaran. Mata pelajaran pada tingkat ini adalah membaca,
menulis, menghafal al-Qur’an serta pengetahuan akhlak. Sehingga, yang menjadi
garis penentu seorang murid dikatakan selesai (lulus) belajar di maktab dan
kuttab ialah guru itu sendiri. Maka, lama belajar setiap murid tidak
sama satu sama lain, karena setiap individu memiliki tingkat kecerdasan yang
berbeda.[26]
Dan yang paling tahu tingkat kecerdasan dari masing-masing murid adalah guru.
Menurut analisis penulis, pelaksanaan pendidikan di maktab
dan kuttab pada pra-Islam dan pada masa awal Islam, tidak jauh berbeda
karena penekanannya tetap pada belajar membaca dan menulis. Hanya saja, hal itu
tidak dapat disamakan begitu saja, terkait dengan kehidupan pra-Islam yang
dikenal dengan masa Jahiliyah sangat berlawanan dengan kehidupan saat Islam
datang dan berkembang. Sehingga, perbedaan yang cukup mendasar terletak pada
substansi yang terkadung dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Substansi
tersebut meliputi tujuan yang ingin dicapai serta penekanan materi yang
diajarkan.
Karakteristik Kuttab Diberbagai Daerah
Rencana
pelajaran yang diberikan di maktab dan kuttab terdiri dari
membaca al-Qur’an serta menghafalnya, pokok-pokok agama, menulis, kisah
(riwayat) orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair,
berhitung, pokok-pokok nahwu dan sharraf. Menurut Yunus dalam Daulay dan Pasa, terdapat perbedaan rencana
pengajaran di maktab dan kuttab pada seluruh Negara Islam, bahkan
berlainan pula di beberapa wilayah. Seperti, di Maghrib (Maroko) hanya
memfokuskan pada pembelajaran al-Qur’an serta dipentingkan pada kepandaian
menulisnya, tanpa diselingi materi-materi yang lain, misalnya hadits, fiqih,
syair dan lain-lain.[27]
Sedangkan di Andalusia diajarkan al-Qur’an
dan menulis serta diajari pula materi-materi lain yaitu syair, pokok-pokok
nahwu, sharaf, dan tulisan indah. Di Afriqiah (Tunisia), pembelajarannya mengarah
pada pelajaran al-Qur’an dengan Hadits dan pokok-pokok ilmu agama, tetapi
menghafal al-Qur’an pada wilayah ini amat dipentingkan. Di Timur (Irak dan
sekelilingnya) sangat mementingkan pelajaran al-Qur’an dan beragam ilmu lainnya
serta kaidah-kaidahnya, tetapi tulisan indah tidak begitu dipentingkan.[28]
Sebagaimana
dikatakan oleh Mehdi Nakosteen bahwa maktab memiliki
arti menjadi lembaga pendidikan dasar pada awal Islam hampir pada setiap kota
dan desa. Selain al-Qur’an dan agama, puisi, kepandaian menunggangi kuda,
berenang, peribahasa terpopular, ilmu hitung dasar, tatabahasa dasar, tatakrama
(adab), dan keahlian menulis indah
semuai itu diajari. Maktab-maktab semacam
itu telah diberlakukan di Spanyol, Sisilia, Afrika, dan Timur Tengah, meskipun
isi dari kurikulumnya berubah disesuaikan dengan sosio-kultural,
kepentingan serta latarbelakang lokasi
tersebut.[29]
Perbedaan penekanan pembelajaran pada maktab dan kuttab, pada dasarnya
disesuaikan dengan daerah tertentu dan pertimbangan para ulama’nya. Kondisi
yang demikian terjadi, khususnya penggunaan al-Qur’an sebagai teks dalam kuttab,
baru terjadi kemudian, pasca ketika jumlah kaum muslimin telah banyak yang
mengusai al-Qur’an, terutama setelah kegiatan kodifikasi hadits pada masa
kekhalifahan Utsman bin Affan. Kebanyakan guru maktab dan kuttab
pada masa awal Islam adalah nonmuslim, sebab muslim yang dapat baca-tulis
jumlahnya masih sangat sedikit dan sibuk dengan pencatatan wahyu.[30]
Bisa juga keadaan yang demikian al-Qur’an belum bisa dijadikan buku teks karena
masih belum terkodifikasi dengan baik menjadi suatu mushaf yang utuh.
Dari berbagai
deskriptif-argumentatif tersebut, baik dari sisi institusi maupun sistem
pengajaran yang diterapkan memberikan implikasi tersendiri sesuai
penekanan dari tiap-tiap wilayah. Maka
dapat dikatakan bahwa maktab dan kuttab sebagai lembaga pendidikan
dasar ini masih berkutat di sekitar
mengenalkan anak dengan ilmu membaca dan menulis al-Qur’an serta prinsip-prinsip
ajaran Islam.[31]
Dan fakta ini juga menjadi bagian dari fakta historis sejarah pendidikan Islam
di masa awal Islam.
Penutup
Berdasarkan deskripsi di atas tentang
pelaksanaan pendidikan dasar di maktab dan kuttab dapat penulis
simpulkan bahwa maktab dan kuttab merupakan lembaga pendidikan
rendah yang sudah ada sebelum Islam datang. Definisi
dari maktab dan kuttab ialah tempat belajar membaca dan menulis.
Akan tetap, sesuai dengan perkembangan zaman, maktab dan kuttab sebagai
lembaga pendidikan juga mengalami perkembangan baik dilihat dari materi yang
diajarkan serta lokasi atau tempat pelaksanaan pendidikan itu sendiri.
Sebagai lembaga pendidikan maktab dan kuttab terdiri
dari unsur-unsur yang bersifat integral dalam rangka mencapai suatu tujuan yang
dimaksud. Unsur-unsur tersebut meliputi kurikulum, tujuan, materi serta tehnik
pembelajaran yang digunakan. Keterpaduan beberapa unsur tersebut memiliki
potensi dalam mewujudkan cita-cita murid sebagai individu yang berkeinginan
untuk tahu dan paham. Dengan demikian, keberadaan maktab dan kuttab
memiliki sisi perbedaan di berbagai wilayah karena, setiap wilayah memiliki kebutuhan
yang berbeda. perbedaan tersebut hanya berkisar pada penekanan pada setiap
materi yang diajarkan.
Daftar
Pustaka
Al-Jumbulati,
Ali dan Abdul Futu at-Tuwānisi. 1994. Perbandingan Pendidikan Islam, terj.
Arifin. Jakarta: Rineka Cipta.
Baharuddin,
et.al. 2011. Dikotomi Pendidikan Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Daulay, Haidar
Putra dan Nurgaya Pasa. 2013. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah:
Kajian dari Zaman Pertumbuhan sampai Kebangkitan. Jakarta: Kencana.
Engku, Iskandar
dan Siti Zubaidah. 2014. Sejarah Pendidikan Islami. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Khaldun, Ibnu.
2009. Muqaddimah. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
Khoiriyah. 2014.
Reorientasi Wawasan Sejarah Islam dari Arab sebelum Islam hingga
Dinasti-dinasti Islam. Yogyakarta: Teras.
Makdisi, George.
1990. Typology of Abad Institutions. London: The Alden Press Limited.
Nasr, Sayyed
Hossein. 1968. Science and Civilization in Islam. Cambridge: Harvard
University Press.
Nata, Abuddin.
2004. Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan. Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada.
.
2012. Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya. Jakarta:
Rajawali Press.
Nizar, Samsul.
2011. Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah
sampai Indonesia. Jakarta: Kencana.
Siswanto. 2013.
Dinamika Pendidikan Islam: Perspektif Historis. Surabaya: CV. Salsabila
Putra Pratama.
Syalabi, Ahmad.
1987. At-Tarbiyatu wa at-Ta’lim fi fikri al-Islam. Kairo: Maktabah
al-Mishriyah.
Zuhairini. 2013.
Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nakosteen, Mehdi. Tt. History of Islamic Origins of Western Education
A.D. 800-1350. Colorado: Colorado Press.
[1] Nama asli Abu
Sufyan bin Umayyah ialah Harb bin Umayyah. Ia adalah tokoh Quraisy yang sangat
terpandang. Pada masanya ia dikenal sebagai saudagar yang unggul yaitu memiliki
jaringan-jaringan perdagangan yang luas ke berbagai daerah, salah satunya
adalah ke Hirah yakni pusat imperium Romawi, Persia dan Irak. Lihat Ibnu
Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2009), 329.
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rahmawati Rahim yang dikutip oleh Mira
Astuti dalam Samsul Nizar. Lihat Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam:
Menelusuri Jejak Serah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2011), 113.
[2] George
Makdisi, Typology of Abad Institutions (London: The Alden Press Limited,
1990), 48.
[3] Nizar, Sejarah
Pendidikan Islam, 113.
[4] Khoiriyah, Reorientasi
Wawasan Sejarah Islam dari Arab sebelum Islam hingga Dinasti-dinasti Islam
(Yogyakarta: Teras, 2014), 88.
[5] Ibid., 51.
[6] Sedangkan
mengenai spesifikasi nama tempat sebagai pelaksanaan belajar baca-tulis, Ahmad
Syalabi mengatakan bahwa tempat pertama pelaksanaan pendidikan dasar di maktab
dan kuttab ialah di rumah-rumah orang yang mengajar, ada yang memang
mengkhususkan satu kamar sebagai tempat pelaksanaan pendidikannya. Namun pada
perkembangan selanjutnya, ketika pembangunan masjid sudah mulai banyak, maka
pembelajaran membaca dan menulis diletakkan di samping-samping masjid, bahkan
ada juga yang diletakkan di sungai, lalu kemudian anak-anak yang belajar
diajari cara berenang, dalam rangka membentuk keterampilan kinestetik, dan
seterusnya. Lihat Ahmad Syalabi, at-Tarbiyatu wa at-Ta’lim fi fikri al-Islam
(Kairo: Maktabah al-Mishriyah, 1987), 48-49. Begitu pula Siswanto
mengungkapkan bahwa pada awal perkembangan Islam, kuttab tersebut dilaksanakan
di rumah-rumah dan pada akhir abad pertama Hijriyah, mulai muncul jenis kuttab
yang tidak hanya mengajarkan materi
baca-tulis, tetapi menluas pada pembelajaran al-Qur’an dan pokok-pokok agama.
Lihat Siswanto, Dinamika Pendidikan Islam: Perspektif Historis
(Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 140.
[8] Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western
Education A.D. 800-1350 (Colorado: Colorado Press, tt),
[9]Sejarah mencatat sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kamil dalam Ahmad
Syalabi mengungkapkan bahwa dalam perang Badar, banyak tentara Makkah yang
menjadi tawanan perang, dan Nabi saw. menjadikan para tawanan khususnya yang
bisa baca-tulis untuk mengajari baca-tulis sekelompok orang Islam sebagai
tebusannya. Syalabi, at-Tarbiyatu wa at-Ta’lim, 48.
[10] Ibid., 47.
[11] Baharuddin,
et.al. Dikotomi Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),
212.
[12]Iskandar Engku
dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), 41.
[13] Syalabi, at-Tarbiyatu
wa at-Ta’lim, 48.
[14] Khoiriyah, Reorientasi
Wawasan Sejarah Islam, 87.
[15] Ibid., 94.
[16] Nizar, Sejarah
Pendidikan Islam, 113.
[17] Ibid.
[18] Ibid., 114.
[20] Ali
al-Jumbulati dan Abdul Futu at-Tuwānisi, Perbandingan Pendidikan Islam, terj.
Arifin (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),, 103.
[21] Baharuddin,
et.al. Dikotomi Pendidikan Islam, 212.
[22] Abuddin Nata, Sejarah
Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2004), 34.
[23] Abuddin Nata, Sejarah
Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya (Jakarta: Rajawali
Press, 2012), 193.
[24] Zuhairini, Sejarah
Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 90.
[25] Ibid.
[27] Haidar Putra
Daulay dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah: Kajian
dari Zaman Pertumbuhan sampai Kebangkitan (Jakarta: Kencana, 2013), 86.
[28] Ibid.
[30] Baharuddin,
et.al. Dikotomi Pendidikan Islam, 212.
[31] Sayyed Hossein
Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge: Harvard University
Press, 1968), 66.




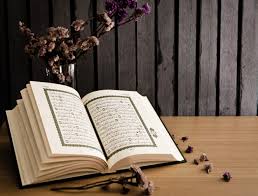
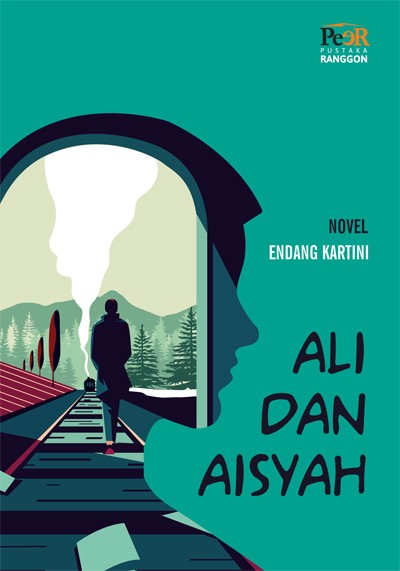






0 Komentar